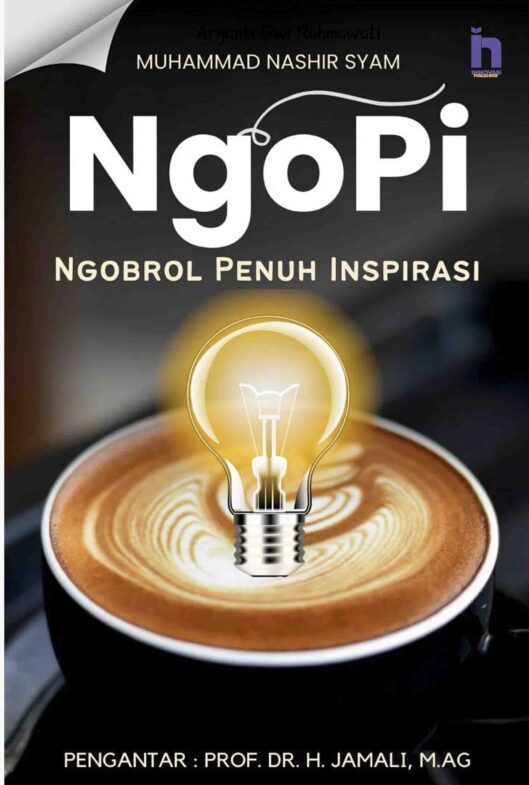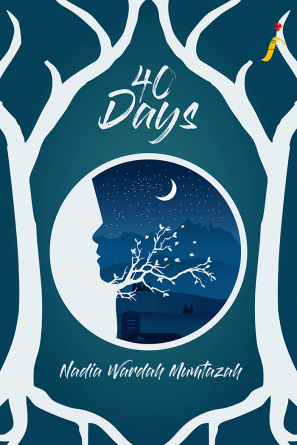Ramadhan 1442 hijriyah. Purnama salah satu malamnya menyala terang, mengusir gulita sekitar belantara di mana saya duduk menatap horizon yang dihiasi pelita kota Buitenzorg nun di arah barat laut sana. Sebuah kota ‘sepenggal surga’ dunia yang disinggahi para kompeni Hullanda sebelum Indonesia hadir dalam kancah dunia.
Setelah menghitung hari yang terus berganti sampai berbilang tahun, malam itu tepat purnama ke lima bulan puasa kami di kampung Maghfirah bersama kawan-kawan yang selalu saya bangga. Seketika memori di kepala memutar ulang hari-hari penuh warna dimulai dari hari pertama sampai pada purtama kelima di malam itu.
Saya berpikir, salah satu harta terbaik saat ini, setelah penjagaan Rabb jalla wa’alaa sehingga atas iman di dada, adalah kawan-kawan setia yang tidak sempurna. Tak sederhana bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, meladeni aneka warna tempaan dan ujian yang melelahkan.
Akan tetapi, walau lelah, kami berharap selalu agar Allah ta’ala mencatatnya sebagai upaya dan usaha yang bernilai lillah.
Doa yang selalu kami panjatkan agar semua ini tak berujung penyesalan; seperti yang dipanjatkan sang komandan pembuka Afrika, Uqba bin Nafi’, “ربنا تقبل منا”
Ba’da doa mulia itu, teringat pesan al Musthafa shallallahu’alaihiwasallam “تهادوا تحابوا” Agar cinta terus bersemi di dada, salah satu formulanya adalah dengan saling bertukar hadiah bermakna.
Dalam senyap malam itu, pertanyaan menanti jawabnya, “hadiah apa yang dirasa paling berharga untuk kawan-kawan yang telah dan masih berjuang bersama menjadi bagian dari para pembuka?” kira-kira apa yang mungkin bertahan cukup lama agar kawan-kawan tak terlupa walau masa masa berganti dan berpindah generasi?
Saya teringat dua legacy para ulama pendahulu yang terus hadir sampai detik ini ada dua, (1) Mata rantai keilmuan yang tak terputus dengan regenerasi pelanjut dan (2) karya tinta pena yang tak lenyap ditelan zaman dan masih bisa dinikmati oleh generasi yang datang kemudian.
Tersebab itulah, saya singkapkan lengan baju, mulai merangkai kata bercerita tentang mereka. Walaupun pada awalnya hadiah ini hanya untuk kawan yang saya bangga yang saya sebut ‘putra Korea’ dan ‘Asgardian’ saja. Tapi, tak mungkin memisahkan keduanya dari kawan-kawan pembuka lainnya. Goresan tinta pena ini adalah hadiah untuk mereka, agar dunia tak melupakannya. ‘MENGEJA PURNAMA’ menabur tinta pena, menggores makna adalah upaya yang saya bisa atas nama cinta dan cita-cita. ربنا تقبل منا
Mewanti Duka
Bismillah
Betapa cepatnya kemesraan yang dulu sempat kita bangun itu berlalu. Kala sunyi terpecah seketika oleh gonggongan anjing penjaga ladang di tepian rimba belantara Gede Pangrango yang hijau membentang menyejuk mata itu.
Saat sebilah sabit rembulan yang beranjak tumbuh dewasa setiap hari, tumbuh dan tumbuh ulet setia dan bersabar hingga menjadi purnama indah di tengah berkah bulan puasa. Tak berselang lama, ia berpamitan pergi tanpa memberi kepastian, akankah esok hari di tahun yang akan tiba nanti berjumpa lagi.
Katanya, dalam sunyi tanpa bunyi, sambil berlalu ia membisiki hati, “yang sempat menghampiri kemarin lusa tak akan pernah kembali seperti sedia kala. Kalaupun ada lagi, dan sempat menghampiri untuk kedua kali, sungguh itu purnama baru”.
Purnama itu segera tiba lagi, dan pasti itu baru. Sebab yang dulu menyapa, itu hanya satu, jika sudah berlalu, ia tak lagi membaru, tapi berlalu dan menjadi debu masa lalu yang melekat di dinding qolbu setiap kita yang merindu purnama baru.
Kampung di kaki Gede Pangrango, tempat tunas-tunas kader guru itu berjibaku dan mengharu biru. Ada rasa rindu yang menggebu kala ingatan akan hari itu mulai mengkristal. Ya, hari pertama bertemu dan hari-hari seru, lika-liku, haru, ragu, lalu bertehan dan maju pernah menjadi satu.
Ada luapan gemuruh qolbu yang ingin sekali bertemu, bercerita tentang aku, kamu, mereka dan kita yang bersatu dengan satu niatan waktu itu; hendak menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi guru. Huuhh, harus teguh dan tangguh agar niat itu tetap kukuh.
Bak seorang ibu yang kehilangan buah hati tercintanya, gumpalan rindu tak berbalas terus menggunung, terus menerus menyeru, “kapankan kita bertemu, doa-doa di tengah terik selalu terseru, panjatan munajat pemecah keheningan malam gulita pun terucap selalu; semoga saja Rabb sang penguasa siang dan malam itu membuka pintu langitNya untuk mengijabahi doa dalam hati dan permohonan terucap di lisan, agar kita berjumpa seperti dulu, bersua saling bercerita dan mendoa. Semoga masa muda kita tak sia-sia, menjelang senja tetap menjadi insan berguna, hari tua saat tulang rangka mulai renta kita berkenan menyicip bahagia di muka; sepenggal bahagia dari surga di hari tua.
Seperti dulu, sekarang dan sampai nanti, di sini kita bersama.
Harapan kepada Rabb alam semesta; semoga ninti kita kembali bersama, bersua dan bertetangga dengan baginda Al Musthafa. Sampai kapanpun kita mesti tetap bersaudara. Ikatan iman perekat jurang pembeda asal dan suku bangsa, iman itulah pengikat kita yang membuat mulia dan persaudaraan ini berujung di Surga.
Perpisahan adalah duka bagi insan yang sejak lama merawat ikat saudara. Agar mata tak terlalu berkaca-kaca saat kekhawatiran itu jadi nyata, maka, kata-kata tentang kawan setia, sahabat tercinta, dan saudara sesurga ini saya tata. Semoga, saat lama tak bersua, saat rindu meronta-ronta ingin bertegur sapa, kelak ada obatnya; membaca tentang mereka, pejuang tangguh, pemuda-pemuda yang mengikis masa mudanya dalam juang mendidik nahkoda bahtera Indonesia. In syaa Alloh. Semua akan indah pada gilirannya.
Rabbanaa laa tuzig quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahablanaa min ladunka rohmah innaka ant al Wahhaab.
Angka-angka Terlupa
“Tentang perjalanan yang belum usai dan belum jua sampai di penghujungnya”
Demikian tulis seorang kawan yang kebiasaannya hanya mengamati peristiwa dari balik asa yang sering tertunda. Dia teringat selalu pada para pemuda yang gegap gempita dari berbagai kota dan desa di bumi persada yang membawa setia cinta dan cita-cita dalam dada mereka ke tepian belantara nun jauh dari gemerlap kota.
Sejarah mencatat berbagai peristiwa dengan detail yang berbeda-beda, walau kadang itu luput dari pena para perawat ingatan, yaitu para sejarawan.
Terkadang yang tercatat itu nama-nama yang terkenang tak terlupa, walau zaman telah lari menjauh meninggalkan hari di mana kita berada saat ini. Tak jarang pula yang selain itu, yaitu angka-angka yang menjadi tanda bahwa aktor-aktor peristiwa itu pernah bersama kita dan menjadi bagian dari cerita yang nanti akan terkenag selalu dan menjadi cerita generasi berikutnya. Ada nama ada angka. Itukah sejarah kita?
Kawan, belajar dari sejarah adalah tabiat orang yang cerdik. Jika peristiwanya dianggap negatif, maka takkan terulang untuk kedua kalinya. Bila sebaliknya, yaitu dalam hal kebaikan, maka akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Begitulah formula-formula kehidupan yang terbimbing wahyu langit itu bekerja, ia membuat manusia yang memahaminya menjadi insan-insan produktif saat singgah di dunia. Selalu saja obsesi mereka agar esok hari lebih baik dari hari ini dan sebelumnya.
Kawan, coba sesekali tengoklah generasi teladan terbaik kita, generasi sahabat nabi dan murid-muridnya. Teguklah segarnya pengalaman dan pengamalan mereka dalam mengemban misi peradaban. Mereka telah kenyang meladeni beraneka warna tantangan kehidupan. Dengan rahmat Allah ta’ala, Al qur’an mengabadikan kisah mereka sebagai manusia-manusia percontohan yang tiada duanya. Begitulah Allah mengganjar manusia-manusia mulia karena imannya.
Mereka dan kita semestinya sama dalam kesadaran akan makna pesan sang pemimpin dan pembimbing teladan yang tiada duanya, Muhammad al Musthafa shallallahu’alaihi wasallam yang mengingatkan:
”لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين”
Pantang seorang beriman itu terjatuh pada lubang kesalahan yang sebelumnya pernah terjerumus di dalamnya. Begitulah semestinya.
Itu formula pertama, lalu formula selanjutnya begini bunyinya,
”…من كان يومه أفضل من أمسه فهو رابح”
Sesiapa yang hari selalu lebih baik dari sebelumnya; itu artinya dia orang roobih, alias beruntung.
Kawan, mungkin salah satu sebab mengapa para pendahulu kita begitu produktif, walau masa aktif mereka untuk tinggal di planet bumi ini tak selama umur yang di tinggali. Tak sesingkat usia bumi itu sendiri. Sebabnya karena mereka ngeh terus, kalau sekarang nggak ada bedanya dengan kemarin lusa, artinya ia rugi. Makanya setiap hari selalu berlomba-lomba untuk lebih baik dari sebelumnya.
Berkaca pada teladan itu membuat kita terpesona. Legacy mereka tak lenyap ditelan masa yang tak henti menjauh menuju usia yang sangat purba. Rohimalloh mereka; para pendahulu kita yang mengerti betul tentang sebuah peluang, mengerti betul kadar diri mereka sendiri,
”rohimalloh imriin ya’rif qodro nafsihi”.
Mari sejenak melihat hari-hari kita dalam ringkasan cerita sejarah singkat perjalanan ini, dari sejak kita tiba, bak drama kolosal yang tak kunjung usai. Episode demi episode berganti dengan warna dan rasa yang selalu berbeda di setiap peristiwanya. Dikatakan ‘sejarah’ karena ia telah berlalu. Tapi dalam dinding hati ia terlukis indah dan selalu membaru.
Sobat, terkadang penikmat sejarah tak begitu memperdulikan deretan nama-nama yang pernah ada dalam suatu peristiwa, juga tak jarang terlewatkan juga tentang angka-angkanya. Mengapa? Sebab tak semua dianggap penting, mereka hanya mencatat yang dianggapnya penting saja. Tapi ingat, itu tidak berlaku bagi para pembuka, anggota rombongan yang tiba sejak pertama di kampung tetangga belantara yang menyimpan kenangan tak terlupa.
Angka-angka itu justru menjadi bagian dari nilai rasa dalam cerita sejarah tentang kampung kita, kampung yang disebut wadi Maghfirah atau lembah Maghfirah di lereng gunung Gede Pangrango yang penuh berkah in shaa Alloh ta’ala.
Kebesaran nama yang meroket ke angkasa dalam waktu singkat mencuat di kancah dunia. Itulah kisah kampung kita, hadiah di muka yang Allah titipkan pada kita.
Realita ini tak berlebihan, karena harapannya memang tidak untuk itu, tapi untuk dikenal apa yang jauh lebih tinggi dari itu semua; dikenal oleh penduduk langit dan tentunya sang penguasa alam semesta, Alloh robbunaa. Dikenal secepat ini oleh banyak warga bumi hanyalah hadiah dimuka dari ilahi di era yang tak ada lagi batas teritorial yang menghalangi. Teknologi informasi memudahkan untuk saling menyapa, walau tak saling berjumpa.
***
Awal cerita cita-cita kampung kita bermula dari kerisauan yang hinggap di kepala para pemikir raksasa yang sangat peduli terhadap masa depan bangsa dan ummat, sampai-sampai pikirannya masygul dan tak mampu beristirahat tenang menyaksikan kenyataan bangsa yang memilukan. Terenyuh hatinya menyaksikan realita umat yang kemuliaannya sering kali tercabik dan tersayat. Bukan karena sedikit jumlahnya, tapi kualitasnya yang sedang diuji. Begitulah kerisauan guru-guru kami yang menggagas kampung kader guru itu.
كثير، لكننا كالغثاء” “, demikian realita berkata. Begitulah saat kualitas tak berbanding lurus dengan kuantitas. Dalam kondisi itulah saatnya berpikir keras, bekerja cerdas membangun integritas.
Kawan, jumlah satuan angka memang bukanlah jaminan atau bahkan sekedar modal pun tidak cukup untuk berjaya. Begitulah kenyataannya. Bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana isi dan kualitasnya.
Belajarlah dari dakwah islam yang sampai di Nusantara, negeri kita tercinta ini. Itu kan ceritanya bermula dari satu sosok saja, nabi kita nabi Muhammad al Musthafa shallallahu’alaihiwasallam. Jumlah yang minoritas, ketika diimbangi dengan kualitas yang tak biasa, maka angka-angka terbatas tak lagi jadi bahan untuk bicara. Artinya, kualitas dan kapasitas berhasil melampaui dan menutupi sisi-sisi kekuarangannya.
Itu semua ketika kita menilik narasi sejarah umat ini pada mula geraknya. Tapi, rupanya zaman kita berbeda. Belajar dari masa-masa mereka tak begitu digalakan di kalangan muda, juga para tetua. Maka angka-angka yang luar biasa pun masih saja biasa; tak bernyawa. Tak mengapa, kebangkitan itu berbeda prosesnya. Tak mesti selalu sama.
Langkah-langkah nyata dimulai dari angka spektakuler bagi lembaga ‘nekad’ di tengah suasana zaman yang kian berwarna tantangannya. Baru dibuka, tercatat 300 anak manusia yang terdaftar sebagai calon mahasiswa di kampus kader guru di tepian belantara itu.
Kala itu, namanya terdengar samar, tapi belum nampak ada di depan kami wujud nyatanya. Saat truk pasir yang menjemput kami tiba, Iya, kami diangkut dengan truk pasir dari villa yang tak ubahnya menjadi persinggahan touris yang mengungsi. Dan mereka adalah kami. Hehe.
Kabarnya, dari angka 300 yang terdaftar di database panitia, sebagian besarnya tak kami temui, sebab tak jadi.
Pada tanggal 25, hari-hari penghujung September 2016, sebuah angka ‘satu’ masuk dalam data panitia berpamitan. Itu artinya satu orang telah memutuskan untuk mengundurkan diri di hari pertama. Dari sekitar 70-an, berkurang terus setiap harinya, dimulai di hari Sabtu. Itu artinya, sejak awal seleksi alam sudah berlaku. Mungkin alasannya karena nggak sesuai ekspektasi. Itu lagu lama kawan.
Satu angka berkurang, berubahlah angka yang pada awalnya kami akan berbangga dengan besarnya jumlah angkatan pertama itu. Jumlah yang ternyata melebihi angka para sahabat angkatan pertama ketika dakwah di mulai oleh Al Musthafa alaihissalam di kota Makkah. Dengan itu kami berencana, suatu hari nanti jumlah ini akan sama-sama berkarya membuktikan kepada dunia bahwa kami eksis ada dan siap memberi manfaat untuk bangsa. Tapi, sejak awal memang ujian kesetiaan itu sudah tiba.
Biarlah, ternyata cerita harus berbeda. Satu orang peserta pulang pagi buta di hari pertama, tanpa pernah sempat berbagi cerita dengan kawan-kawan barunya. Padahal rangkaian acara yang disusun rapi oleh panitia sudah siap dilaksanakan dengan saksama. Kawan yang satu itu tak mau berpikir lama, mungkin dia mengira begini, “di sini tidak sesuai ekspektasi; tak seperti yang dikira” atau mungkin ada sekian alasan alasan sebagai senjata tak terbantahkan untuk ‘say.. bye-bye’.
Setelah menghitung hari dengan jari-jari kami. Angka lama berganti menjadi sekitar 70 an saja. Ohh.., betapa cepatnya sebuah siklus perubahan angka-angka matematika tentang cerita sejarah awal kampung kami, kampung yang kita bangga nanti. Ya, kita akan bangga dengan adanya kampung ini, karena pernah menjejak sebelum beranjak ke sudut bumi lainnya. Rabbanaa taqobbal minnaa.
Sekitar sebulan lamanya karantina para calon mahasiswa kader guru itu berlangsung. Ternyata setelah syaikh kami, guru asing super keren asal Afrika itu tiba dari Malaysia, angka angkatan pertama itu kembali berubah dengan derastisnya. Bukan bertambah, tapi berlanjut ke bawah. Syaikh kami merasa keheranan, “kok bisa?”.
Sekitar setengahnya saja atau lebih sedikit yang tersisa. Apakah kandas lalu putus asa karena angka yang tak lagi seperti di hari pertama? Jawabannya ternyata “TIDAK”. “Kita lanjut saja!” tekad kawan-kawan membaja. Seperti pepatah orang Bugis bilang, “bila layar terkembang pantang surut ke tepi”. Proyek besar pengkaderan guru dan murobbi itu HARUS tetap dilanjutkan, sekalipun yang tersisa hanya satu orang saja.
Perjalanan singkat, cerita ‘tumbang’nya kawan-kawan seangkatan terus berlaku. Ada rasa khawatir yang sangat, bagaimana jadinya, andai yang tersisa hanya satu saja. Huuh, jangan sampai. Yang tersisa harus bertekad agar ‘masuk bersama lulus bersama’, bukan keluar bersama. Entahlah, takt ahu apa yang akan terjadi esok lusa. Yang penting usaha menjaga tekad baja para pembuka itu tetap menyala.
***
Suatu hari, di tahun 2017, salah seorang guru kami, termasuk founder father-nya ide kampus kader guru ini juga. Dalam kelas berdinding anyaman bambu berseni tinggi, tiba-tiba pagi menjelang siang itu beliau melontarkan kata-kata yang tak terduga, nampak bercanda, tapi justru menjadi nyata, ”antum mungkin akan tinggal tersisa 25 orang saja”, Ooo, ternyata melenceng, tapi melampaui itu, justru tersisa 23 saja. Lalu menjadi 22, 21… dst.
Kawan-kawan yang ada sampai detik ini, mereka masih setia bersama di sini, di kampung harapan yang menjadi mimpi besar guru kami sang murobbi yang belum mampu kami teladani; Dr.Ahmad Hatta, MA. Saat ini angka ini hanya tingal 18 saja. Alhamdulillah masih ada setia merawat asa dan cita-cita.
Semoga mereka, kawan-kawan setia itu menjadi kesatria yang tangguh dan kukuh mengemban amanah, dari menjadi pembuka hingga menjadi para raksasa. Begitulah, mereka memang sejak awal berpijak di atas pundak para raksasa, para guru yang tak lekas menyerah saat membina mereka yang rentang meladeni problema masa muda.
Mereka menjadi besar bukan untuk berbangga, tapi untuk terus membuka jalan-jalan kebaikan yang tak terhingga, yang sebagiannya masih rapat tertutup dan menjadi rahasia Rabb alam semesta.
Menjadi kesatria dan raksasa itu tidak untuk hari ini, tapi akan datang masanya nanti. in shaa Allah. Semua akan indah pada gilirannya. Tak perlu tergesa-gesa.
Kawan, mari berdoa, semoga Allah menjaga angka yang tersisa dan tak jadi bagian dari daftar angka-angka yang terlupa. Amin.
Baarokallohufiikum ayyuhal ahibbaa.
Semoga Allah menganugerahi hati-hati kita keikhlasan yang tak usang ditelan masa. Harapan terbesar, seperti berbilang tahun kita bersama, semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama al Musthafa di surga.
Sobat, catat! Kita bangga menjadi santri di kampung impian sang murobbi, Dr. Ahmad Hatta ini. Bagaimana tidak, sejarah mencatat, arus perjuangan bangsa ini dalam meraih kemerdekaan dulu, tak lepas dari perjuangan dan pengorbanan santri dan para ulama.
“Santri Never Die” begitulah kira-kira motto juang mereka, dan semoga kita juga. Di manapun kaki berpijak, engkau tetaplah santri, tetaplah bermanfaat dan berkontribusi hingga akhir hayat nanti. Negeri ini masih setia menanti peranmu sebagai santri dalam membangun Indonesia tercinta ini.
Sahabat=Fasilitator=Inisiator
Kawan, setiap kita tidak ada yang tahu (sama sekali) isi dari catatan qolam yang menuliskan takdir dalam lembar catatan makhluk-makhluk penduduk bumi ini; tentang masa depannya, dan juga soal detail-detail peristiwa yang nantinya jadi kenangan indah atau payah dalam memori masa tua.
Maka, yang terpenting bagi kita yang tidak diberi tahu tentang rahasia yang takkan dibuka ini adalah selalu berharap yang terbaik. Mengusahakan yang maksimal dengan harapan bejodoh dengan makna pesan Al Musthafa shallallahualaiahiwasalam, ”Kullun muyassarun limaa khuliqo lah”.
***
Setelah kembali dengan selamat dari tugas mulia bersama kawan-kawan di ujung timur Indonesia, tepatnya di bumi Animha, bertetangga dengan Papua New Guinea. Tibalah saatnya, kawan kami itu untuk mudik ba’da bulan puasa. Kembali ke Jawa, bersua dengan keluarga tercinta. Kembali ke tanah Jawa bukan berarti selesai cerita. Justru cerita baru kembali dimulai, “Tentang kita” kata kawan kami. Tentang para pembuka kampung baru tempat kader guru-guru umat dibina.
Betul, dari situlah justru dimulai cerita sejarah mereka. “Di saat banyak sejarawan menuliskan sejarah masa lampau, rasanya kami ingin dan sudah memulai menulis cerita ‘sejarah’ masa depan kita dalam lembaran kehidupan nyata”, tulis seorang kawan angkatan pertama.
Ingin mencatat yang terlalui dari peristiwa-peristiwa itu sebagai pijakan untuk catatan sejarah masa depan. Bukan tenggelam dalam khayalan, tetapi berimajinasi dalam merancang alur yang akan dilalui. Sepertinya begitu bunyi isi hatinya. Betul-betul begitu? Entahlah.
Lanjutnya, “kami hendak menjadi narator dan perawi sejarah masa depan kami dan Indonesia tercinta, juga umat yang sedang merangkak bangkit berjaya”. Belum usai, kembali dilanjutkannya, “Tentang kita, wahai kawan, ingin rasanya suatu hari nanti, dan itu kita mulai dari saat ini, kita ingin membuat yang rumit menjadi harmoni, dan membuat yang berserak menjadi tertata rapi”. Ada harapan besar dari guru-guru muda generasi ‘Santri Never Die’ ini.
Setiap momen besar yang terealisasi tak terlepas dari peran yang biasanya berada di belakang layar. Tak nampak, tapi sangat berdampak. Sebut saja dalam kata-kata mutiara yang sering diangkat tentang peran perempuan dalam membesarkan para laki-laki untuk berkontribusi, bisa jadi seorang ibu atau pun ibunya ibu atau yang selainnya. Selain mereka, ada yang lain yang berjasa dalam cerita perjalanan setiap insan dalam menapaki tangga-tangga menuju puncak cita. Mereka tak lain adalah sahabat-sahabat kita.
Kawan, sahabat-sahabat setia, mereka tanpa diminta bekerja dalam sunyi, agar pintu yang tertutup dan dibaliknya ada jalan berundak-rundak membentang menuju puncak itu dapat kita lalui. Maka, jadilah sahabat kita pembuka pintu itu. Jadilah mereka para inisiator dan fasilitator jalan kita dalam menapaki tangga-tangga. Merekalah pahlawan kita tanpa deklarasi sebelum tindakan nyata dan bukti dalam realita. “Khidmatul ashaab syarofun lanaa” begitulah motto menyala dalam dada sahabat setia kita.
***
Di tahun 2014 adalah titik awal cerita seorang kawan, setelah ia kembali dari Papua, lalu bertemu di kampung baru untuk memulai kembali merangkai sebuah alur cerita perjalanan. Sebenarnya setelah kepulangannya dari timur Indonesia itu, ia berkesempatan study di kampus arab di Sukabumi, tapi rupanya stasiun persinggahan yang menyatukan kita bukan di sana, tapi pada persinggahan setelahnya; di kampus kader guru ini.
Setelah tiba saatnya untuk menapaki warna hidup baru di tepian timur Jawa, tepatnya pada 2016, bersentuhanlah kawan kita dengan warna sosial para pemakmur kota asal Madura. Tak lama, singkat saja. Takdir berkata bahwa kawan kami itu harus kembali ke kampung halamannya, mesti bertemu dengan para pejuang muda, para murobbi teladan kami.
Sebelum itu, sesampainya ia di kampus ‘miniatur’ universitas Madinah di timur Jawa itu, ia meneguk kesegaran ilmu dan petuah dari para ulama, juga dari tentara yang menempanya seharian di penghantar menuju awal perkuliahan di kampus itu. Ada peran sahabat yang rela berkorban di tengah kesibukan, menyempatkan mengurusi proses tibanya kawan ini.